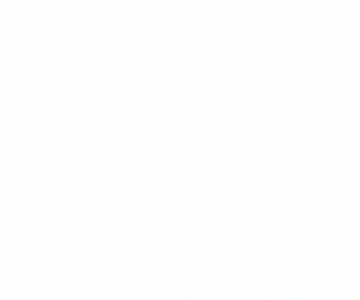Oleh : Heintje Mandagi / Ketua Dewan Pers Indonesia
Baru-baru ini ‘Kuburan’ Kemerdekaan Pers kembali terisi ‘jasad’ karya jurnalistik. Kali ini ‘batu nisan’ kemerdekaan pers itu bertuliskan nama Muhammad Asrul, wartawan media online Berita.News yang divonis bersalah dengan hukuman pidana 3 bulan penjara akibat karya jurnalistik.
‘Roh’ kebebasan pers milik Asrul ini pada akhirnya menyatu dengan jasad Udin wartawan Bernas dan Muhammad Yusuf wartawan Kemajuan Rakyat. ‘Kuburan’ kemerdekaan pers milik Torozidu Lahia, wartawan Harian Berantas yang belum juga kering.
Kini sudah terisi lagi ‘jasad’ kemerdekaan pers milik Asrul. Kasus kriminalisasi pers yang dialami keduanya itu seolah-olah menyatu dengan ratusan ‘Roh’ kebebasan pers milik wartawan di berbagai penjuru tanah air yang terkubur di ‘pekuburan’ umum Kemerdekaan Pers Indonesia yang dibangun penguasa tunggal bernama Dewan Pers.
[irp]
Berkaca dari kasus Torozidu Lahia, wartawan Harian Berantas yang memberitakan kasus korupsi Bupati Bengkalis, justeru dihadiahi PPR Dewan Pers yang menyatakan media Harian Berantas tidak terverifikasi Dewan Pers dan Torozidu belum mengikuti Uji Kompetensi Wartawan.
Dan dengan entengnya Dewan Pers merekomendasi penyelesaian perkara tersebut dapat dilakukan di luar Undang-Undang Pers.
Ujung-ujungnya Torozidu dipenjara, meskipun kemudian dinyatakan bebas murni. Namun sang Bupati Bengkalis akhirnya terbukti korupsi dan ditangkap KPK, serta divonis bersalah dan dihukum penjara sesuai perbuatannya sebagaimana apa yang pernah ditulis Torozidu di Harian Berantas.
Ini bukti tulisan berita Torozidu benar tapi diganjar PPR Dewan Pers melanggar kode etik.
Di penghujung 2018 lalu, almarhum Muhamad Yusuf, wartawan Kemajuan Rakyat dan Sinar Pagi Baru pun mengalami nasib yang sama diproses hukum pidana di luar UU Pers setelah PPR Dewan Pers diterbitkan.
Yusuf tewas dalam tahanan. Meregang nyawa dalam status sebagai tersangka akibat karya jurnalistiknya. Kasus serupa juga dialami ratusan wartawan di berbagai daerah.
Kasus di atas memang berbeda dengan apa yang dialami Muhammad Asrul. Dewan Pers melakukan pembelaan dan menyatakan kasus Asrul harus diproses menggunakan UU Pers.
Namun, polisi dan jaksa tetap meneruskan kasus tersebut hingga ke pengadilan. Dewan Pers pun menghadirkan saksi ahli. Namun majelis hakim tetap memvonis Asrul bersalah dan dipidana 3 bulan penjara.
Lantas apa yang dilakukan Dewan Pers pasca putusan vonis Asrul tersebut adalah membuat surat pernyataan keprihatinannya. Tidak ada langkah luar biasa untuk mengatasi persoalan serius terkuburnya kemerdekaan pers ini.
Isi surat pernyataan Dewan Pers terkait kasus Asrul tidak ada menyebutkan perjuangan organisasi pers tempat Asrul bernaung. Seakan-akan semua hanya mengenai Dewan Pers.
Polisi, jaksa, dan hakim yang terlibat perkara Asrul ini seharusnya dilaporkan ke lembaganya masing-masing untuk diberi sanksi karena tidak profesional menangani perkara pers.
Faktanya juga, organisasi pers tidak hadir di kasus Asrul. Padahal sebagai wartawan, Asrul wajib dilindungi oleh organisasi pers tempat dia bernaung. Hal itu karena organisasi pers tidak diberi ruang sedikitpun untuk mendampingi atau membela kepentingan Asrul di Dewan Pers.
Ketika Asrul dilaporkan, Organisasi Pers tidak hadir. Dewan Pers yang maju sebagai pahlawan. Tapi sayangnya rekomendasi Dewan Pers terlalu ‘banci’ dan maaf ‘abal-abal’ alias tak berkualitas.
UU Pers sudah jelas Lex Specialis. Jadi, ketika wartawan dilaporkan, harus ada tindakan tegas meminta kepolisian menghentikan penyidikan dan melimpahkan penanganan perkara pers ke Dewan Pers.
Sebagaimana lazimnya penanganan perkara dilimpahkan ke tingkatan yang sesuai dengan lokasi kejadian. Hal itu pun seharusnya berlaku di perkara pers.
Karena kewenangan itu ada di Dewan Pers untuk menyelesaikan perkara pers, maka pihak kepolisian wajib melimpahkan berkas perkara ke Dewan Pers.
Apapun alasan kepolisian untuk menerima aduan perkara pers dibalut UU ITE harus dihormati tapi perlu dikritisi.
Karena Pers memiliki UU Pers yang melindungi kemerdekaan pers sebagai wujud perlindungan hakiki terhadap hak asazi manusia yang diakui dunia internasional. Tak heran Indonesia selalu berada di urutan menengah ke bawah dalam hal kebebasan pers internasional.
Jika sekelas Dewan Pers tunduk kepada Kepolisian, padahal penanganan perkara pers adalah kewenangannya, maka apa gunanya Dewan Pers hadir sebagai lembaga independen jika tidak mampu bersikap menjalankan amanah UU Pers.
MOU Dewan Pers dengan Polri sesungguhnya adalah bentuk pelecehan terhadap UU Pers. Pers seolah mengemis perlindungan hukum kepada polisi yang jelas-jelas hal itu adalah kewajiban Polri memberi jaminan perlindungan hukum kepada setiap warga negara.
Organisasi pers yang menjadi induk pembinaan dan perlindungan pers sudah dirampas haknya oleh supremasi Dewan Pers.
Setiap kasus perkara pers, tidak ada organisasi pers yang dihadirkan untuk melakukan pembelaan dan pembinaan, atau bahkan melewati tahapan sidang majelis kode etik di masing-masing organisasi pers, sebagai wadah tempat wartawan bernaung dan berlindung.
Mediator ‘abal-abal’ yang dihadirkan Dewan Pers dalam menangani aduan pers pun hampir seluruhnya tidak bersertifikat resmi sebagai mediator. Padahal setiap mediator harus bersertifikat dan disahkan Pengadilan.
Akibatnya, wartawan yang menjadi pihak teradu selalu berada pada posisi lemah dalam penanganan perkara pers.
Seharusnya penyelesaian perkara pers bukan PPR Dewan Pers yang jadi hasil akhir. Namun harus berdasarkan kesepakatan antara pengadu dan teradu. Bukan keputusan penilaian Dewan Pers.
Itulah fungsi mediator dalam penanganan perkara pers, agar tidak ada kriminalisasi pers.
Dewan Pers juga, faktanya, tidak membuka akses bagi masyarakat yang dirugikan akibat pemberitaan di seluruh Indonesia, untuk menampung pengaduan. Dampaknya, warga masyarakat yang dirugikan pers terpaksa harus mengadu atau melapor ke Polisi.
Dan ketika diproses pidana UU ITE dan pidana pencemaran nama baik, penyidik Polri dari seluruh Indonesia harus meminta PPR Dewan Pers di Jakarta yang anggotanya hanya berjumlah 9 orang saja.
Tidak ada sikap Dewan Pers meminta pelimpahan penanganan perkara pers, ke Dewan Pers agar tidak ada kriminalisasi.
Sejatinya, pengadu dapat diberi keleluasaan untuk mendapatkan pelayanan hak jawab. Dan teradu yakni pimred media wajib menjalankan pemenuhan hak jawab teradu dan kewajiban koreksi.
Peran mediator yang harus hadir di situ. Sayang sekali penyelesaian perkara ini hanya terhenti di PPR Dewan Pers. Dan kasus tetap berlanjut di kepolisian. UU Pers jadi memble atau tidak berfungsi. Peran organsiasi pers pun sama, yaitu tidak pernah diberi ruang.
Organisasi pers sebagai wadah tempat wartawan bernaung pun tidak pernah menyelesaikan perkara pers menggunakan tahapan sidang majelis kode etik dan pemberian sanksi.
Peraturan Dewan Pers tentang Kode Etik Jurnalistik, menjadi tidak berlaku atau tidak berguna tanpa implementasi karena semua terpusat di Dewan Pers. Padahal yang paling paham tentang anggota wartawan pastinya adalah pimpinan organisasi pers.
Atas kondisi di atas, sudah barang tentu kesimpulan akhir harus disematkan kepada Dewan Pers, yaitu gagal total dan tidak berguna dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga independen yang ditugaskan menjamin kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional.
Tak heran Uji Materi Undang-Undang Pers di Mahkamah Konstitusi, menjadi satu-satunya jalan keluar dari kegagalan Dewan Pers. Harus ada keputusan dan penilaian objektif Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi melihat persoalan ini.
Norma yang terkandung dalam UU Pers khususnya Pasal 15 Ayat (2) huruf f tentang fungsi Dewan Pers yang berbunyi “Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan“ harus dimaknai menjadi :
“Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers oleh masing-masing organisasi pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan” agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.
Dan juga tidak menghilangkan fungsi dan kewenangan organisasi pers membuat peraturan pers untuk melindungi anggota wartawan dan perusahaan pers.
Buntut uji materi di MK, muncul reaksi berlebihan dari kelompok konstituen Dewan Pers.
Ada pandangan hukum yang menyebutkan, uji materi UU Pers ini adalah kesesatan pikir dari pemohon dan jika dikabulkan akan menyebabkan ketidakpastian hukum dan dapat menimbulkan peraturan-peraturan pers yang bersifat terpisah, sporadis, dan justeru bertentangan dengan kemerdekaan pers.
Dewan Pers yang tak berdaya melawan kriminalisasi pers terhadap Asrul dan bahkan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses kriminalisasi pers terhadap media yang belum terverifikasi dan wartawan yang belum UKW.
Kelompok pers yang termarjinalkan juga sulit berkembang di berbagai daerah dengan stigma negatif media abal-abal dan wartawan abal-abal.
Media Terverifikasi dan UKW menjadi jualan Dewan Pers untuk meraup untung dari bisnis UKW ilegal dan pengelompokan media terverifikasi.
Segelintir pemilik media yang belum berbadan hukum dijadikan senjata pamungkas Dewan Pers untuk memotret puluhan ribu media online dengan stigma media abal-abal.
Celakanya, pemerintah daerah ikut terbius dengan propaganda negatif Dewan Pers tersebut, kemudian menerbitkan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah yang mewajibkan kerja sama perusahaan pers dengan pemerintah daerah harus terverifikasi Dewan Pers.
Kendati pada prakteknya, media terverifikasi Dewan Pers tidak ada jaminan memiliki jumlah pembaca organik dan banyak, serta konten beritanya berkualitas.
Buktinya, baik rating media dan perolehan pendapatan iklan komersil masih jauh dari kata mencukupi biaya operasional. Wartawan yang bekerja di media terverifikasi masih begitu banyak yang tidak digaji. Dewan Pers pura-pura tutup mata dan gak tau apa-apa.
Padahal monopoli belanja iklan oleh konglomerat media sudah berlangsung selama belasan tahun di negeri ini. Media dan pers lokal termarjinalkan tanpa solusi dari Dewan Pers.
Ratusan triliun rupiah belanja iklan pertahun hanya dinikmati segelintir konglomerat media nasional.
Lebih parah lagi, pendapatan media mainstream nasional berjumlah triliunan rupiah per tahun tapi wartawannya masih jauh dari kata sejahtera.
Sialnya, organisasi pers konstituen Dewan Pers hanya organisasi AJI yang konsisten berteriak sendiri soal batas minimal gaji wartawan pemula berada diangka 9 juta rupiah perbulan.
Meski angka tersebut masih terlalu sedikit dibanding taruhan independensi wartawan tergadaikan akibat nyambi terima amplop dari nara sumber.
Seharusnya, gaji wartawan level reporter yang bekerja di media nasional peraih pendapatan triliunan rupiah, wajib menggaji wartawannya di angka 15 juta rupiah.
Belum lagi peraih belanja iklan nasional itu adalah media televisi nasional yakni di angka 80 persen. Lembaga riset Media Business Nielsen Indonesia mencatat, nilai belanja iklan tahun 2020 di Indonesia sebesar Rp229 triliun di semua tipe media yang dimonitor, yakni TV, Cetak, Radio dan Digital.
Dan Nielsen menyebutkan, media TV masih menjadi ruang beriklan yang paling dominan yakni di atas 70 persen dari Rp229 triliun belanja iklan tahun 2020 lalu.
Berkaca dari kondisi ini, perlu dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
Pasal 17 ayat (3) UU Penyiaran menyebutkan, “Lembaga Penyiaran Swasta wajib memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memiliki saham perusahaan dan memberikan bagian laba perusahaan.
Kemudian pada ketentuan pidana Pasal 57 huruf a. Disebutkan,” Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3)” dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
Untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi.
Pada UU Pers juga diatur tentang kesejahteraan wartawan pada Pasal 10 yakni: “ Perusahaan Pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya.
Nah, kedua UU tersebut di atas sudah sangat jelas mengatur tentang pemberian kesejahteraan terhadap karyawan, (termasuk wartawan pada UU Penyiaran) dan kepada wartawan dan karyawan pers (pada UU Pers).
Lantas di mana kehadiran Dewan Pers dan organisasi konstituen Dewan Pers, terkait perjuangan hak-hak wartawan dan karyawan pers di media mainsream nasional. Jangankan pemberian saham atau pembagian laba, wartawan di media penyiaran swasta nasional saja masih ada wartawan yang tidak digaji tapi hanya dibayar berdasarkan jumlah berita yang ditayangkan di siaran berita televisi.
Koresponden atau kontributor TV nasional di daerah, banyak yang mengalami nasib tidak digaji tapi hanya dibayar per berita tayang.
Muncul pertanyaan besar, adakah Dewan Pers dan organisasi konstituen IJTI melaporkan pidana pemilik Lembaga Penyiaran Swasta Nasional yang melanggar ketentuan pidana Pasal 57 huruf a. UU Penyiaran ?
Lembaga Penyiaran Swasta, wajib memberikan bagian laba perusahaan dan jika melanggar kewajiban ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi.
Kemudian adakah Dewan Pers sebagai lembaga yang diakui negara memperjuangkan hak-hak wartawan untuk mendapatkan kesejahteraan dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya dari pemilik perusahaan pers ?.
Kondisi ini yang menjadi perhatian serius organisasi-organisasi pers, di luar konstituen Dewan Pers untuk membentuk Dewan Pers Indonesia yang independen dalam rangka memperjuangkan hak-hak wartawan dan media tersebut yang terabaikan.
Dewan Pers Indonesia, sudah bertekad untuk memperjuangkan kepentingan perusahaan-perusahaan pers lokal agar bisa mendapatkan porsi iklan komersil. Agar tidak ada lagi media lokal ‘mengemis’ iklan kerja sama dengan pemerintah daerah.
Dan belanja iklan nasional yang mencapai ratusan trililun rupiah itu, bisa terdistribusi ke seluruh daerah di Indonesia. Ke dapan nanti tidak boleh ada monopoli perusahaan agensi iklan yang hanya menyalurkan belanja iklan kepada media-media televisi nasional.
Dewan Pers Indonesia saat ini, sedang berjuang membina puluhan media online berbasis SEO Google agar bisa meraup untung dari belanja iklan di google yang cukup besar.
Di tahun 2022, ada program Dewan Pers Indonesia melalui Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia (DPP SPRI) membina lebih banyak lagi media berstandar SEO Google. Targetnya 1000 media online di 2022 sudah terpasang SEO Google pro.
Dengan cara ini tidak ada lagi pemerintah bekerja sama hanya dengan media terverifikasi Dewan Pers. Karena media yang terpasang SEO Google pro pasti akan lebih berkualitas dibanding media terverifikasi Dewan Pers, karena rating dan jumlah pembacanya pasti organik dan jauh lebih banyak dari media yang terverifikasi Dewan Pers.
Jika seluruh media online lokal terdampak dengan program pemasangan SEO Gogle premium ini maka diperkirakan belanja iklan akan terbagi ke seluruh Indonesia atau tidak lagi dimonopoli oleh media nasional yang berada di Jakarta saja. Karena kualtas media sudah merata di seluruh Indonesia.
Mengingat legitimasi Dewan Pers Indonesia belum juga disahkan oleh Persiden RI Joko Widodo maka sangat diharapkan permohonan uji materi UU Pers, khususnya Pasal 15 Ayat (3) bisa dikabulkan majelis hakim MK.
Permohonan itu menyatakan Pasal 15 ayat (3) UU Pers bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai :
“Keputusan presiden bersifat administrasi sesuai usulan atau permohonan dari organisasi-organisasi pers , perusahaan-perusahaan pers dan wartawan yang terpilih melalui mekanisme kongres yang demokratis.”
Penulis adalah Ketua Dewan Pers Indonesia, Ketua Umum DPP SPRI, dan Ketua LSP Pers Indonesia.
[*to-65].
[irp]